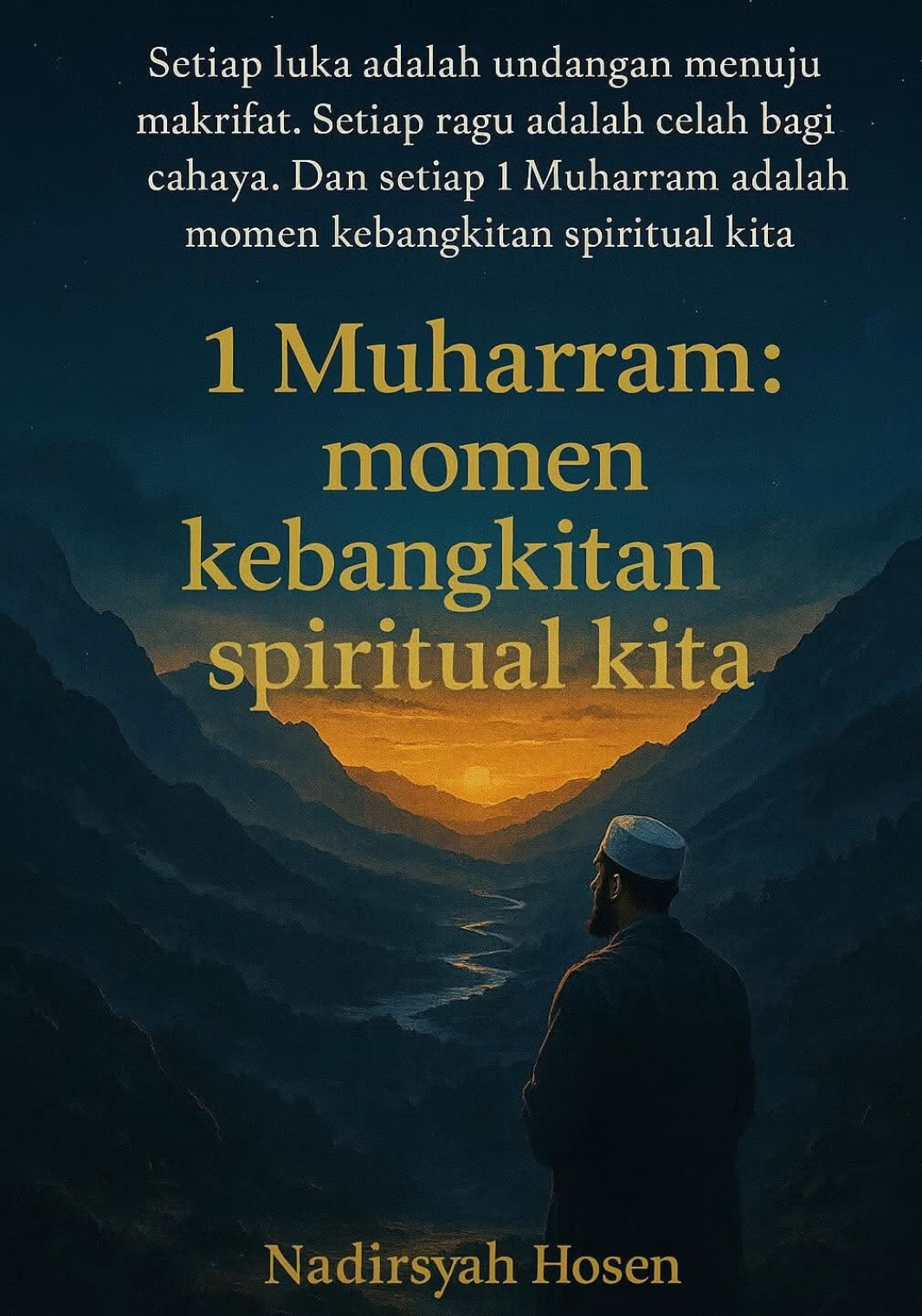Halaltoday.id- Setelah menempuh perjalanan panjang, dengan tubuh letih dan hati penuh harap, para jamaah akhirnya sampai ke Mekah—rumah suci, pusat kiblat, tanah yang disebut Allah sebagai “Umm al-Qura”.
Namun justru pada puncak haji, mereka tidak tinggal di Masjidil Haram. Mereka disuruh keluar, menjauh. Meninggalkan Ka’bah untuk pergi ke Arafah—sebuah padang luas di luar kota suci.
Baca juga:
Tentang Ulang Tahun, dan Tentang Kita yang Terlalu Mudah Mengharamkan
Kenapa?
Karena haji bukan sekadar ziarah ke Ka’bah. Haji adalah perjalanan menuju kesadaran. Dan Arafah—yang berasal dari akar kata ‘arafa (mengenal)—adalah tempat di mana manusia harus mengenali dirinya, Tuhannya, dan sesama manusia.
Di sanalah, kata Nabi, “al-Ḥajju ‘Arafah”—inti haji adalah Arafah. Bukan thawaf. Bukan mencium Hajar Aswad. Tapi berdiri dalam keheningan spiritual, dalam kerendahan dan pengakuan di hadapan Yang Maha Melihat.
Ali Shariati melihat haji sebagai drama teologis dan sosial. Baginya, keluar ke Arafah adalah simbol eksodus spiritual—keluar dari pusat ritual ke padang eksistensi.
Ia menulis:
“Pergi ke Arafah adalah keluar dari rumah Tuhan untuk bertemu Tuhan di alam semesta. Di sana manusia berdiri, bukan di hadapan Ka’bah, tapi di hadapan diri sendiri.”
Dalam perspektif sufistik, perjalanan ke Arafah adalah fana’—sirna dari ilusi bentuk-bentuk luar.
Para sufi melihat Ka’bah bukan sebagai titik akhir, tetapi sebagai panggilan awal. Arafah adalah maqam ma’rifah—tingkatan di mana sang salik melepaskan ego dan topeng dunia.
Di sana, jiwanya tajalli—tersingkap dari hijab. Sebab untuk mengenal Tuhan, seorang hamba harus lebih dulu mengenal diri, sebagaimana sabda: “Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu.”
Di Arafah, hanya langit, angin, dan jiwa yang telanjang. Maka, jangan heran jika setelah sampai ke rumah Tuhan, engkau justru disuruh keluar.
Sebab hanya mereka yang pernah berdiri di Arafah—dalam sunyi, jujur, dan sadar—yang layak kembali ke Ka’bah dengan hati yang telah pulang lebih dulu.
Tabik,
Nadirsyah Hosen